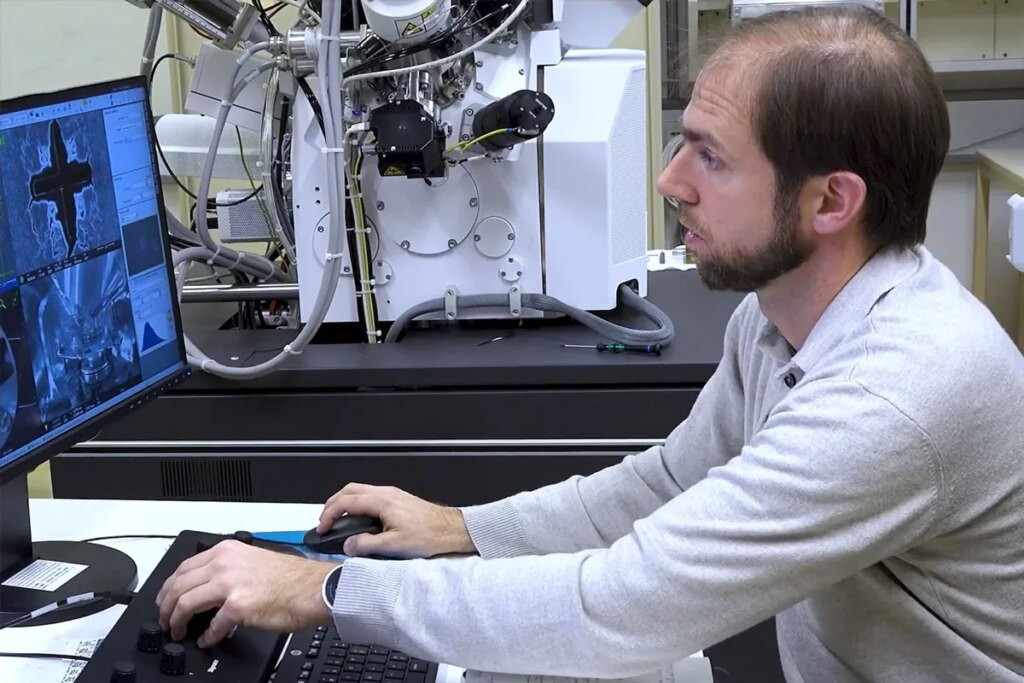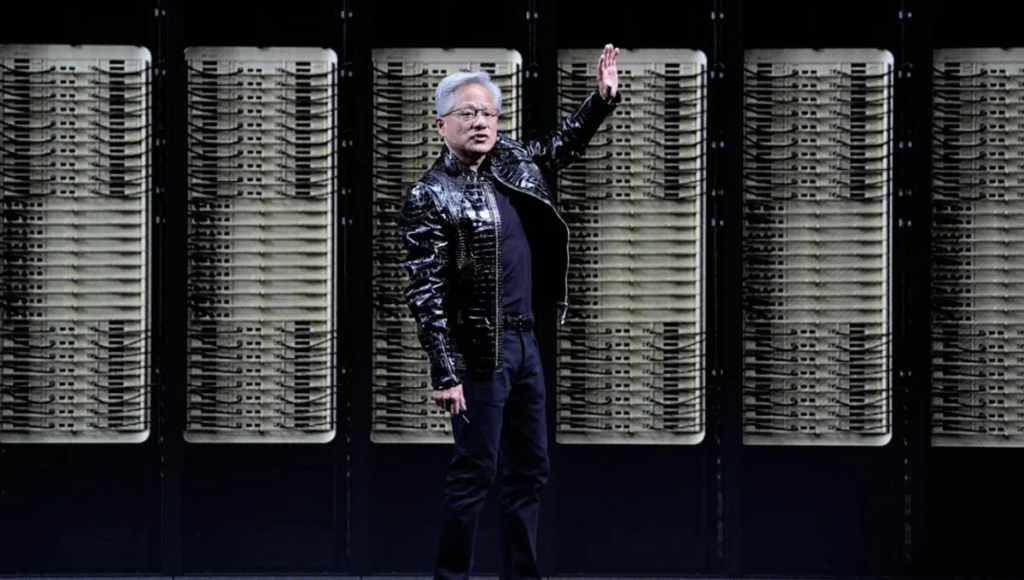Perkembangan pesat layanan digital dinilai telah mengubah wajah industri telekomunikasi secara fundamental. Namun, perubahan besar tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pembaruan regulasi.
Kondisi inilah yang mendorong pelaku industri seluler di Indonesia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aturan telekomunikasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan realitas industri saat ini.
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyoroti masih dibebankannya Biaya Hak Penggunaan (BHP) kepada operator telekomunikasi, meski layanan komunikasi suara kini bukan lagi monopoli operator seluler.
Sekretaris Jenderal ATSI, Merza Fachys, menilai kebijakan tersebut tidak lagi mencerminkan ekosistem digital yang telah berkembang sangat dinamis.
Merza menegaskan bahwa perubahan pola konsumsi masyarakat telah menggeser posisi layanan suara dari layanan eksklusif menjadi komoditas umum.
Dalam forum Indonesia Digital Outlook 2026 di Jakarta Kamis (29/01/2026), ia menyampaikan, “Layanan telepon, layanan komunikasi suara itu sudah merupakan bukan layanan telekomunikasi, sudah merupakan komoditi yang kita bisa gunakan tanpa usaha.”
Saat ini, layanan komunikasi suara dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi berbasis internet. Platform global seperti Google, Telegram, Facebook, hingga aplikasi lokal telah menghadirkan fitur panggilan suara tanpa mengandalkan layanan telepon konvensional.
Namun, kewajiban pembayaran BHP tetap hanya ditujukan kepada operator telekomunikasi, sementara pemain digital tidak memiliki kewajiban serupa.
Merza menilai kondisi ini menciptakan ketimpangan yang semakin nyata. Ia menambahkan, “Telepon sudah bukan punyanya telekomunikasi, sayangnya masih ada BHP yang dibebankan ke operator telekomunikasi.”
Menurutnya, ketidakseimbangan tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan industri dalam jangka panjang.
Alih-alih terus meminta insentif, industri justru mendorong pemerintah untuk meninjau ulang regulasi yang dianggap sudah usang. Evaluasi ini dipandang lebih penting agar industri dapat tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan tetap mampu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur digital nasional.
Merza menegaskan, “Mari kita lihat evaluasi hal-hal seperti ini, banyak yang harus kita pilah pilih karena banyak regulasi yang macamnya seperti itu.”
Pandangan serupa disampaikan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). Ketua Bidang Industri IoT, AI & Big Data Mastel, Teguh Prasetyo, menilai penyedia konektivitas saat ini belum memperoleh manfaat yang seimbang dari kehadiran platform digital dan aplikasi over-the-top (OTT).

Padahal, operator seluler memikul beban besar dalam membangun dan menjaga infrastruktur jaringan nasional. Menurut Teguh, kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan industri telekomunikasi untuk meningkatkan investasi. Ia menilai kebutuhan industri sebenarnya tidak berlebihan.
“Enggak besar mintanya teman-teman telco, sehingga bisa balik lagi ke double digit, teman-teman telco sehat lagi,” ujarnya.
Dengan kondisi industri yang sehat, operator diharapkan mampu kembali menggenjot investasi jaringan.
Di sisi lain, isu ketimpangan juga muncul dari perspektif penerimaan negara. Peneliti ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Dyah Ayu, menilai kontribusi fiskal dari perusahaan digital global belum sebanding dengan besarnya aktivitas ekonomi yang mereka hasilkan di Indonesia.
Ia menyebut pendapatan perusahaan digital global di Indonesia mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.
Dyah menilai model perpajakan saat ini masih tertinggal dari realitas ekonomi digital. “Kita bisa mengambil pajak dari seberapa besar pengguna aktif, misalnya pengguna aktif TikTok, pengguna aktif Netflix maupun pengguna aktif dari Instagram itu sendiri,” ujarnya. Menurutnya, pajak digital berbasis aktivitas ekonomi dapat menjadi solusi yang lebih adil.

Pembahasan regulasi telekomunikasi juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Teguh Prasetyo menilai pembangunan ekosistem AI di Indonesia masih berada pada tahap awal, terutama dari sisi infrastruktur. Ia menilai pembangunan GPU dan pusat data AI di Indonesia tumbuh sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Ke depan, AI diproyeksikan menjadi pendorong utama adopsi jaringan 5G. Teguh bahkan menyebut AI sebagai killer application berikutnya.
“Kalau ditanya killer application 4G apa, jawabannya e-commerce. Kalau 5G, kami melihat AI akan menjadi killer application-nya,” tegasnya.
Namun, pemerintah juga mengingatkan adanya risiko global yang menyertai lonjakan investasi teknologi. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Sonny Hendra Sudaryana, mengingatkan potensi terjadinya gelembung ekonomi.
“AI bubble ini terjadi ketika investasi yang dikeluarkan belum menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan,” ujarnya, merujuk pada hasil diskusi World Economic Forum 2025.
Dari sisi operator, Merza Fachys menegaskan bahwa AI bukan hanya isu telekomunikasi, melainkan bagian dari industri digital secara menyeluruh.
“AI ini dimainkan oleh hampir semua industri, bukan hanya operator,” katanya. Saat ini, operator memanfaatkan AI untuk efisiensi jaringan dan layanan enterprise, bukan sebagai produk ritel yang dimonetisasi langsung.
Sementara itu, Dyah Ayu menilai investasi AI di Indonesia tetap akan tumbuh seiring besarnya potensi pasar domestik. “Ini bukan cuma AI yang menjawab pertanyaan, tapi AI yang terus update dan bisa menjadi search engine sekaligus analis,” ujarnya, merujuk pada perkembangan agentic AI.
Dengan penetrasi internet yang telah melampaui 80 persen populasi, Indonesia dinilai memiliki daya tarik kuat bagi investor global. Oleh karena itu, pembaruan regulasi telekomunikasi dan kebijakan pajak digital menjadi kunci agar pertumbuhan industri berjalan adil, sehat, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Foto: Katikjoe
Scr/Mashable